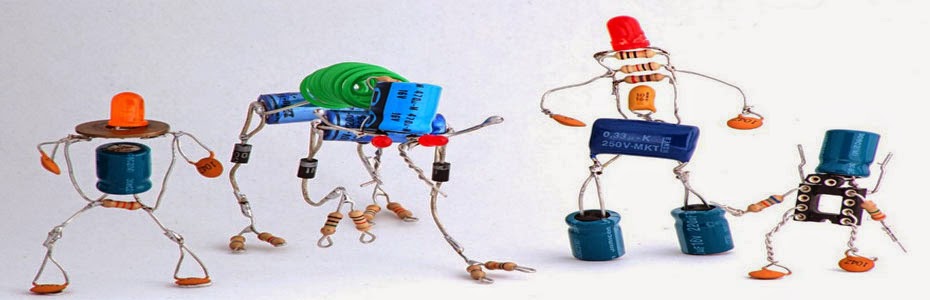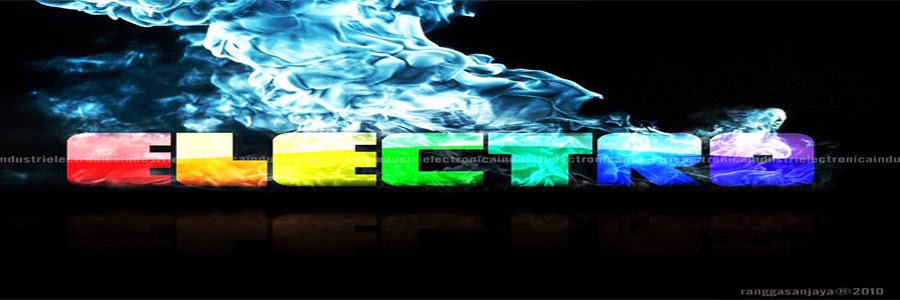ARTIKEL BAHAN AJAR
A. DEFINISI BAHAN AJAR
Bahan Ajar adalah sebuah persoalan pokok yng tidak bias dikesampingan dalam satu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar.
Menurut National Centre for Competency Based Training (2007), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. (Sumber : Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012).
B. PENTINGNYA MEMBUAT BAHAN AJAR
Pada pentingnya bahan ajar, berkaitan pada fungsi, tujuan, dan kegunaan bahan ajar. Karena kita tidak akan mampu memahami pentingnya bahan ajar jika, tidak mengetahui ketiga komponen tadi. (Sumber : Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012).
1. Fungsi Bahan Ajar :
a. Fungsi Bahan Ajar Menurut pihak yang memanfaatkan Bahan Ajar.
Berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar, fungsi bahan ajar, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik.
1) Fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain:
a) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar;
b) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator;
c) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif;
d) Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik; serta
e) Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.
2) Fungsi bahan ajar bagi peserta didik, antara lain;
a) Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain;
b) Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki;
c) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri;
d) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri;
e) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar/mahasiswa yang mandiri; dan
f) Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya.
b. Fungsi Bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan.
Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, fungsi dalam pembelajaran individual, dan fungsi dalam pembelajaran kelompok.
1) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain;
a) Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran (dalam hal ini, peserta didik bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan pendidik dalam mengajar); dan
b) Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan.
2) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain;
a) Sebagai media utama dalam proses pembelajaran;
b) Sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi; serta
c) Sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya.
3) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain;
a) Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan cara memberikan informasi tentang latar-belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri; dan
b) Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivaasi belajar siswa.
2. Tujuan Pembuatan Bahan Ajar
Untuk tujuan pembuatan bahan ajar, setidaknya ada empat hal pokok yang melingkupinya, yaitu;
a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu;
b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik;
c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran; dan
d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.
3. Manfaat Pembuatan Bahan Ajar
Adapun manfaat atau kegunaan pembuatan bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kegunaan bagi pendidik dan kegunaan bagi peserta didik.
a. Kegunaan bagi pendidik.
Setidaknya, ada tiga kegunaan pembuatan bahan ajar pagi pendidik, diantaranya sebagai berikut:
1) Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
2) Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat.
3) Menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan.
b. Kegunaan bagi peserta didik
Apabila bahan ajar tersedia secara bervariasi, inovatif, dan menarik, maka paling tidak ada tiga kegunaan bahan ajar bagi peseerta didik, diantaranya sebagai berikut:
1) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik;
2) Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik;dan
3) Peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya.
(Sumber : Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012)
C. TUJUAN BAHAN AJAR
Seperti dipaparkan sebelumnya, bahwa Tujuan Bahan Ajar ialah;
a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu;
b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik;
c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran; dan
d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.
(Sumber : Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012)
D. SUMBER – SUMBER BAHAN AJAR
Sumber Belajar adalah bahan mentah untuk penyusunan bahan ajar. Jadi, untuk bias disajikan kepada peserta didik, sumber belajar harus diolah terlebih dahulu. (Sumber: Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012).
Sumber-sumber bahan ajar dapat disebutkan di bawah ini:
1. Buku Teks
Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apa lagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Gunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat memperoleh wawasan yang luas. Buku teks merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang ilmu tertentu. Oleh karena itu, buku teks pada umumnya mempunyai komponen dan kriteria, di antaranya adalah mengasumsikan minat dari pembaca, ditulis untuk pembaca (guru, dosen), dirancang untuk dipasarkan secara luas, belum tentu menjelaskan tujuan instruksional, disusun secara linear, stuktur berdasar logika bidang ilmu, belum tentu memberikan latihan, tidak mengantisipasi kesukaran belajar siswa, belum tentu memberikan rangkuman, gaya penulisan naratif tetapi tidak komunikatif, sangat padat, kurang mengakomodir mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari pembaca.Buku teks yang baik tentu saja buku teks yang mampu menyedia-kan sebuah sumber dan bahan belajar yang kom preensif serta dapat mengakomodir terciptanya proses pem belajaran yang baik sesuai tujuan yang diharapkan.
2. Laporan Hasil Penelitian
Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir.
3. Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah)
Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya.
4. Pakar Bidang Studi
Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar. Pakar tadi dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dsb.
5. Profesional
Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Kalangan perbankan misalnya tentu ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Sehubungan dengan itu bahan ajar yang berkenaan dengan eknomi dan keuangan dapat ditanyakan pada orang-orang yang bekerja di perbankan.
6. Buku Kurikulum
Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Karena berdasar kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah yang harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci.
7. Penerbitan Berkala
Penerbitan berkala seperti koran banyak berisikan informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Penyajian dalam koran-koran atau mingguan menggunakan bahasa popular yang mudah dipahami. Karena itu baik sekali apabila penerbitan tersebut digunakan sebagai sumber bahan ajar.
8. Internet
Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita dapat memeroleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi.
9. Media Audiovisual (TV, Video, VCD, kaset audio)
Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi, kehidupan di laut, di hutan belantara melalui siaran televisi.
10. Lingkungan ( alam, sosial, senibudaya, teknik, industri, ekonomi)
Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lengkungan seni budaya, teknik, industri, dan lingkungan ekonomi dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar. Untuk mempelajari abrasi atau penggerusan pantai, jenis pasir, gelombang pasang misalnya kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai sebagai sumber bahan ajar.
(Sumber : http://panduanguru.com/sumber-bahan-ajar-jenis-dan-contohnya/)
Referensi :
Praswoto Andi, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012, Diva Press, Jogjakarta.
http://panduanguru.com/sumber-bahan-ajar-jenis-dan-contohnya/
A. DEFINISI BAHAN AJAR
Bahan Ajar adalah sebuah persoalan pokok yng tidak bias dikesampingan dalam satu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar.
Menurut National Centre for Competency Based Training (2007), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. (Sumber : Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012).
B. PENTINGNYA MEMBUAT BAHAN AJAR
Pada pentingnya bahan ajar, berkaitan pada fungsi, tujuan, dan kegunaan bahan ajar. Karena kita tidak akan mampu memahami pentingnya bahan ajar jika, tidak mengetahui ketiga komponen tadi. (Sumber : Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012).
1. Fungsi Bahan Ajar :
a. Fungsi Bahan Ajar Menurut pihak yang memanfaatkan Bahan Ajar.
Berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar, fungsi bahan ajar, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik.
1) Fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain:
a) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar;
b) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator;
c) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif;
d) Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik; serta
e) Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.
2) Fungsi bahan ajar bagi peserta didik, antara lain;
a) Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain;
b) Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki;
c) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri;
d) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri;
e) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar/mahasiswa yang mandiri; dan
f) Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya.
b. Fungsi Bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan.
Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, fungsi dalam pembelajaran individual, dan fungsi dalam pembelajaran kelompok.
1) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain;
a) Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran (dalam hal ini, peserta didik bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan pendidik dalam mengajar); dan
b) Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan.
2) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain;
a) Sebagai media utama dalam proses pembelajaran;
b) Sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi; serta
c) Sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya.
3) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain;
a) Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan cara memberikan informasi tentang latar-belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri; dan
b) Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivaasi belajar siswa.
2. Tujuan Pembuatan Bahan Ajar
Untuk tujuan pembuatan bahan ajar, setidaknya ada empat hal pokok yang melingkupinya, yaitu;
a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu;
b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik;
c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran; dan
d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.
3. Manfaat Pembuatan Bahan Ajar
Adapun manfaat atau kegunaan pembuatan bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kegunaan bagi pendidik dan kegunaan bagi peserta didik.
a. Kegunaan bagi pendidik.
Setidaknya, ada tiga kegunaan pembuatan bahan ajar pagi pendidik, diantaranya sebagai berikut:
1) Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
2) Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat.
3) Menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan.
b. Kegunaan bagi peserta didik
Apabila bahan ajar tersedia secara bervariasi, inovatif, dan menarik, maka paling tidak ada tiga kegunaan bahan ajar bagi peseerta didik, diantaranya sebagai berikut:
1) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik;
2) Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik;dan
3) Peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya.
(Sumber : Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012)
C. TUJUAN BAHAN AJAR
Seperti dipaparkan sebelumnya, bahwa Tujuan Bahan Ajar ialah;
a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu;
b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik;
c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran; dan
d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.
(Sumber : Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012)
D. SUMBER – SUMBER BAHAN AJAR
Sumber Belajar adalah bahan mentah untuk penyusunan bahan ajar. Jadi, untuk bias disajikan kepada peserta didik, sumber belajar harus diolah terlebih dahulu. (Sumber: Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012).
Sumber-sumber bahan ajar dapat disebutkan di bawah ini:
1. Buku Teks
Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apa lagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Gunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat memperoleh wawasan yang luas. Buku teks merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang ilmu tertentu. Oleh karena itu, buku teks pada umumnya mempunyai komponen dan kriteria, di antaranya adalah mengasumsikan minat dari pembaca, ditulis untuk pembaca (guru, dosen), dirancang untuk dipasarkan secara luas, belum tentu menjelaskan tujuan instruksional, disusun secara linear, stuktur berdasar logika bidang ilmu, belum tentu memberikan latihan, tidak mengantisipasi kesukaran belajar siswa, belum tentu memberikan rangkuman, gaya penulisan naratif tetapi tidak komunikatif, sangat padat, kurang mengakomodir mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari pembaca.Buku teks yang baik tentu saja buku teks yang mampu menyedia-kan sebuah sumber dan bahan belajar yang kom preensif serta dapat mengakomodir terciptanya proses pem belajaran yang baik sesuai tujuan yang diharapkan.
2. Laporan Hasil Penelitian
Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir.
3. Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah)
Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya.
4. Pakar Bidang Studi
Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar. Pakar tadi dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dsb.
5. Profesional
Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Kalangan perbankan misalnya tentu ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Sehubungan dengan itu bahan ajar yang berkenaan dengan eknomi dan keuangan dapat ditanyakan pada orang-orang yang bekerja di perbankan.
6. Buku Kurikulum
Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Karena berdasar kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah yang harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci.
7. Penerbitan Berkala
Penerbitan berkala seperti koran banyak berisikan informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Penyajian dalam koran-koran atau mingguan menggunakan bahasa popular yang mudah dipahami. Karena itu baik sekali apabila penerbitan tersebut digunakan sebagai sumber bahan ajar.
8. Internet
Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita dapat memeroleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi.
9. Media Audiovisual (TV, Video, VCD, kaset audio)
Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi, kehidupan di laut, di hutan belantara melalui siaran televisi.
10. Lingkungan ( alam, sosial, senibudaya, teknik, industri, ekonomi)
Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lengkungan seni budaya, teknik, industri, dan lingkungan ekonomi dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar. Untuk mempelajari abrasi atau penggerusan pantai, jenis pasir, gelombang pasang misalnya kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai sebagai sumber bahan ajar.
(Sumber : http://panduanguru.com/sumber-bahan-ajar-jenis-dan-contohnya/)
Referensi :
Praswoto Andi, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: 2012, Diva Press, Jogjakarta.
http://panduanguru.com/sumber-bahan-ajar-jenis-dan-contohnya/